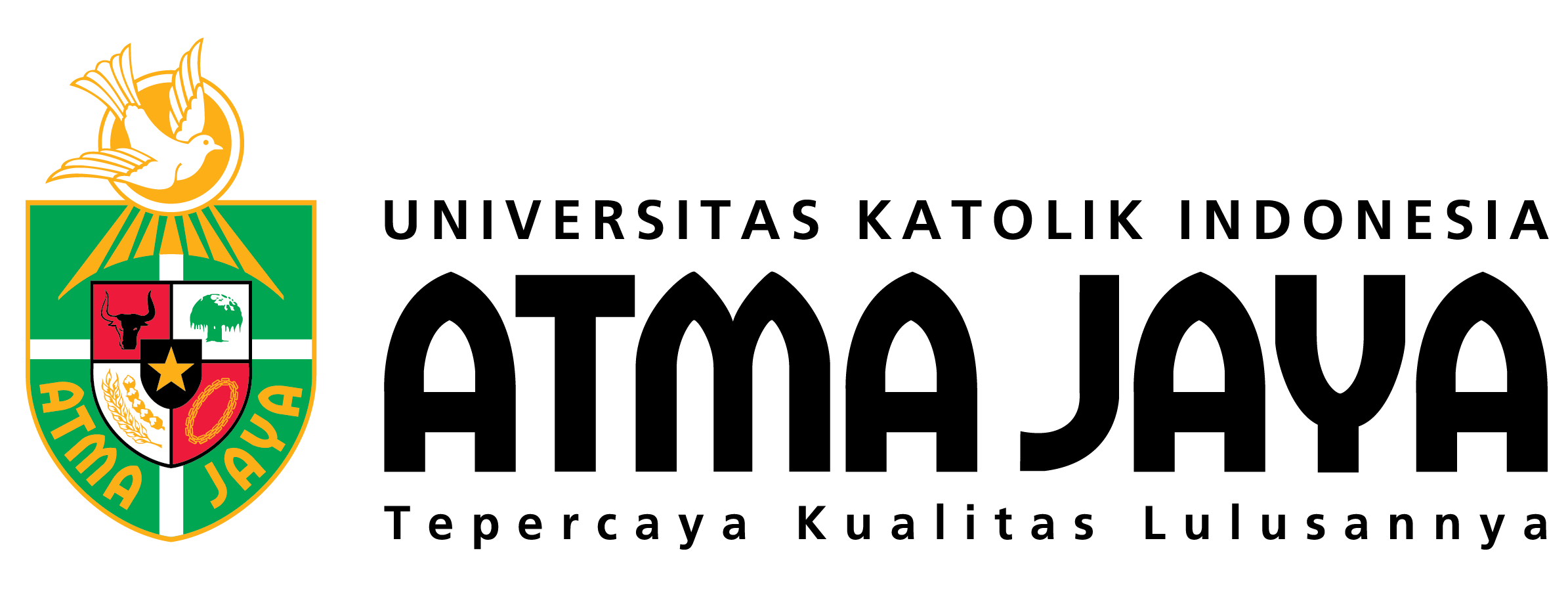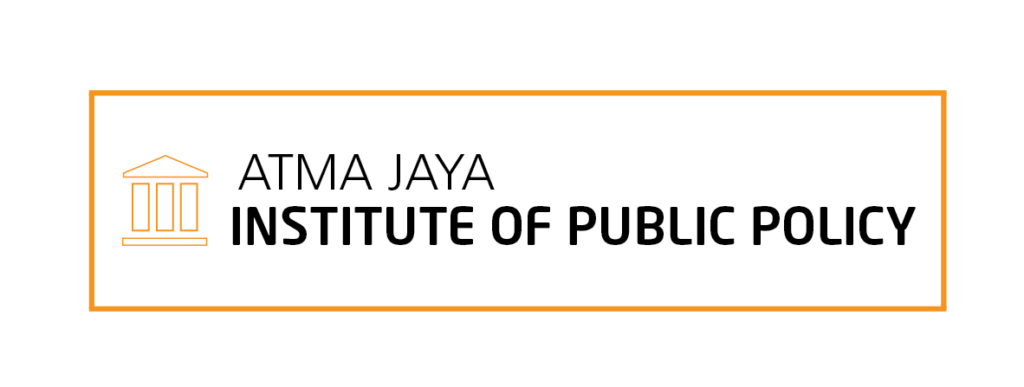Laporan Berkelanjutan 2022: Transformasi untuk Berkelanjutan

Laporan Keberlanjutan Unika Atma Jaya 2022, berisi informasi, data, dan penjelasan yang bersifat material bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Unika Atma Jaya. Informasi, data, dan penjelasan Laporan ini berasal dari dan merujuk pada beragam dokumen dan narasumber internal yang mengelola dan memiliki otoritas atasnya. Kecuali disebut khusus, sebutan ‘Unika Atma Jaya’ merujuk pada tiga lokasi kampus yang dimiliki, yaitu Semanggi, Pluit, dan Bumi Serpon Damai (BSD) Serpong, di bawah otoritas yang menaunginya. Dengan demikian, penyebutan Unika Atma Jaya mewakili eksistensi keseluruhan kampus di lokasi-lokasi yang berbeda. Laporan ini memakai dua perspektif waktu. Pertama, perspektif existing condition, yang menangkap fenomena waktu kini dan waktu lalu dalam bentang tiga tahun (2019-2021) untuk merekam dan menganalisis kinerja Unika Atma Jaya dari dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kedua, perspektif masa depan melalui pernyataan-pernyataan yang bersifat forward-looking. Unika Atma Jaya menyadari bahwa risiko dan ketidakpastian dari berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal, telah dan akan memberi pengaruh pada kinerja operasional dan kondisi penyelenggaran pendidikan dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh sebab itu, setiap informasi, data, dan penjelasan dalam dua perspektif waktu itu—existing condition dan forward-looking—perlu disikapi hati-hati untuk tidak menimbulkan salah pengertian dan dispute. Kontributor Laporan: Pengarah: Tema Ekonomi: Tema Lingkungan: Tema Sosial
Brownbag Discussion: Menuju 2024: “Politik Dinasti Tak Berbatas?”

Demokrasi Indonesia dewasa kini tidak lepas dari dinasti politik yang bertolak belakang dengan prinsip reformasi. Dinasti politik dianggap sebagai dampak dari lemahnya pelembagaan partai politik dan tidak berjalannya fungsi partai politik. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan menguatnya kekerabatan dalam birokrasi yang kerap dikenal sebagai nepotisme. Pasalnya, pemilik parta partai bisa saja lebih mengutamakan kerabatnya dibanding calon lain yang lebih kompeten. Kekerabatan dalam jejaring politik di pemerintahan berpotensi memudahkan lolosnya kepentingan predatoris sehingga kesempatan politik dan ekonomi tidak terbagi secara relatif adil untuk masyarakat. Dinasti Politik membuka ruang dan melapangkan jalan terjadinya korupsi. Hingga saat ini terdapat enam dinasti politik yang terlibat dalam pusaran korupsi. Keenam dinasti politik itu adalah Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten, Syaukani Hassan Rais di Kutai Kartanegara, Atty Suharti di Cimahi, Fuad Amin Imron di Bangkalan, Sri Hartini di Klaten, dan Yan Anton Ferdian di Banyuasin. Sejatinya, akan selalu ada dinasti politik dalam tubuh demokrasi Indonesia. Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri bahkan sebagai presiden sekalipun, termasuk seseorang yang memiliki kerabat di pemerintahan. Bisa dikatakan, praktik dinasti politik adalah wujud dari aji mumpung atau privilese yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat menyebabkan kekuasaan hanya berpusat pada keluarga (dinasti) tertentu. Institute of Public Policy Unika Atma Jaya berkolaborasi dengan LP3ES akan mengadakan Brownbag Discussion: Menuju 2024: “Politik Dinasti Tak Berbatas?” Narasumber: Moderator:
Brownbag Discussion: Menuju 2024: Ancaman Hoaks pada Pemilu 2024 (12 Oktober 2022)

14 Februari 2024 merupakan tanggal pemungutan suara untuk pemilu 2024.Menuju Pemilu 2024, salah satu dinamika yang sering kita alami adalah beredarnya hoaks terkait politik dan pemilu. Hoaks adalah upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menjelang perhelatan pemilu kita sering menemui narasi-narasi politik yang bertujuan menjatuhkan calon tertentu. Kominfo mencatat hoaks politik mendominasi dengan jumlah 549 temuan dari 1.610 temuan hoaks selama periode Agustus 2018-23 April 2019. Maret 2019 menjadi puncak tertinggi peredaran hoaks, yakni mencapai 453 isu hoaks (Katadata, 2019). Mengingat pemilu 2019 yang diselenggarakan pada bulan april, Dari data tersebut kita dapat melihat hoaks politik semakin banyak beredar ketika mendekati pemilu. Beredarnya hoaks melalui sosial media rentan menciptakan konflik sosial-politik karena hoaks beredar dengan mudah secara maya. Media sosial memang berguna untuk menghubungkan konstituen dan calon peserta pemilu, tapi media sosial juga dapat berguna untuk menyebarkan informasi tidak benar dan memicu konflik di masyarakat. Banyak masyarakat kesulitan membedakan berita bohong ataupun negara. Kurangnya literasi dan pengetahuan membuat masyarakat dengan mudah percaya terhadap hoaks. Oleh karena itu, untuk mencari strategi membendung hoaks pada pemilu 2024, kita dapat mempelajari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya. Kebijakan terkait pengendalian hoaks dalam media sosial perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut meminimalisir dampak hoaks selama pemilu berlangsung. Narasumber: Moderator:
Bedah Buku: CIPALI (Trans-Jawa dan Tol Enam Presiden dengan Sembilan Rahasianya)

Tol Cikopo – Palimanan atau Cipali, gagasan untuk pembangunannya sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Hal ini tercatat dalam Dinas Bina Marga Kabupaten Subang sejak 1996. Eksekusi pembangunannya berhenti karena krisis moneter 1998. Jalan Tol ini kembali dibangun presiden ke-4 setelah Soeharto lengser, Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden ke-6 Indonesia. SBY mulai melanjutkan proyek Tol Cipali pada 2011 lalu. Jalan Tol Cipali sudah berada dalam 6 era kepresidenan di Indonesia. Proyek yang dijanjikan rampung pada 2015 ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi sebulan sebelum waktu yang dijanjikan. Dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi, pembangunan tol cipali memakan waktu yang sangat lama. Berbagai hambatan ditemui diantaranya pembebasan lahan dan pembiayaan proyek. Terkait dengan pembebasan lahan pembangunan tol cipali pada prinsipnya mencoba menerapkan prinsip tidak merugikan rakyat dan negara, berusaha menemukan titik temu antara harga jual yang diminta masyarakat sekitar dan taksiran harga yang wajar negara bukanlah hal yang mudah. Perjalanan pembangunan jalan tol Cipali yang panjang dituliskan dengan baik pada buku “Cipali Trans-Jawa dan Tol Enam Presiden dengan Sembilan Rahasianya”. Dalam acara bedah buku ini akan dibahas awal perjalanan, tantangan dalam pengadaan lahan dan pembiayaan serta pengalaman yang bisa diambil dari pembangunan tol Cipali. Narasumber Sandiaga Uno – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Stefanus Ginting- Mantan Direktur Proyek PT Lintas Marga Sedaya Iu Rusliana – Dosen Filsafat UIN Sunan Gunung Djati dan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Agustinus Prasetyantoko – Rektor Unika Atma Jaya Eko Djoeli Heripoerwanto – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Achmad Gani Fhazaly Akman – Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Rudy Susanto – Direktur Bank Central Asia Hari : Senin, 28 Juni 2021 Waktu : 11.00-13.00 Publikasi:
Policy Brief dari IPP di T20 Indonesia

Terbitnya Policy Brief dari IPP di T20 Indonesia merupakan hasil dari pengalaman IPP dalam berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Society (IFSOC) dalam memperkuat peran dan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Sebagai organisasi yang fokus pada kebijakan publik, IPP memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam terkait dengan isu-isu kebijakan yang relevan dan penting untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan di Indonesia. Penulis Atma Jaya yang Terlibat: Arief C Nugraha – IPP Atma Jaya Selengkapnya: https://www.t20indonesia.org/wp-content/uploads/2022/11/TF2_Towards-Digital-Empowerment-of-MSMEs-1.pdf
Population Ageing and the Second Demographic Dividend: New Policy Challenges in the New Era

Terbitnya Policy Brief dari IPP di T20 Indonesia merupakan hasil dari upaya IPP dalam memperkuat peran dan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Policy Brief yang dihasilkan mengambil tema dari Atma Jaya Outlook for Development 2022, yaitu kesejahteraan warga lanjut usia sebagai tantangan kebijakan kini dan nanti. Melalui policy brief ini, IPP bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan solusi terkait isu yang krusial ini, dan membantu para pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi warga lanjut usia di Indonesia. Penulis: Selengkapnya: https://www.t20indonesia.org/wp-content/uploads/2022/11/TF5_Population-Ageing-and-The-Second-Demographic-Dividend-New-policy-Challenges-in-The-New-Era.pdf
Atma Jaya Outlook for Development 2022: Kesejahteraan Warga Lanjut Usia Tantangan Kebijakan Kini dan Nanti

Institute of Public Policy, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 20/12, meluncurkan `the Atma Jaya’s Outlook for Development 2022’. Outlook ini mengambil tema `Kesejahteraan Warga Lanjut Usia: Tantangan Kebijakan Kini dan Nanti’ dalam empat dimensi, yakni kesehatan, teknologi, psikososial, dan hukum. Peluncuran Outlook diselenggarakan melalui webinar yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto, S.Si. Dalam sambutannya Wakil Rektor menyatakan Outlook ini menunjukkan kiprah dan kepedulian Unika Atma Jaya atas isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. “Outlook ini diharapkan dapat menjadi sumber gagasan dan pemikiran bagi kebijakan mengenai warga lanjut usia,” kata Yohanes Eko. Outlook ini sendiri menunjukkan bahwa demografi Indonesia mencatat tanda-tanda penuaan. Data Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan, dari 270,2 juta penduduk Indonesia, hampir 10 persen di antaranya tergolong warga lanjut usia, yakni penduduk di atas umur 60 tahun. Ini berarti ada sekitar 27 juta jiwa warga lanjut usia di Indonesia. Jumlah ini masih lebih besar daripada jumlah penduduk gabungan tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jumlah ini juga sekitar lima kali lebih besar daripada total penduduk Singapura atau mendekati total penduduk Malaysia. Satu dekade lalu total penduduk lansia baru 18 juta jiwa. Jadi ada tambahan sembilan juta jiwa lansia baru dalam 10 tahun terakhir, atau 900 ribu jiwa per tahun. Saat ini kelompok umur ‘lansia muda’ (60-70 tahun) masih mendominasi keseluruhan penduduk lansia, yakni mendekati 65 persen. Kelompok `lansia madya’ mencakup 27 persen dari keseluruhan lansia Indonesia, sedangkan `lansia tua’ sekitar sembilan persen. Komposisi ini berubah dari satu dekade lalu, ketika lansia muda, madya, dan menengah mengambil prosi berturut-turut 59,59, 30,12, dan 10,29 persen dari keseluruhan lansia. Outlook Atma Jaya ini juga merekam isu kesehatan kontemporer tentang lansia. Meski lansia diprioritaskan dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19, capaiannya masih di bawah yang diharapkan, bahkan tertinggal dari capaian di kelompok umur 12-17. Hingga 18 Desember 2021 vaksinasi pertama bagi lansia baru menjangkau 60 persen populasi lansia, sedangkan vaksinasi kedua 39 persen. Pada kelompok umur 12-17 tahun vaksinasi pertama dan kedua masing-masing telah mencapai 87 dan 60 persen. Outlook ini mencatat tiga penyebab, yakni (1) keterbatasan mobilitas lansia dalam mengakses program vaksinasi, (2) keterbatasan lansia untuk mengakses informasi, dan (3) banyak berita palsu yang beredar. “Pemerintah perlu lebih aktif lagi. Bukan menunggu datang ke pusat layanan, tapi mengunjungi lansia ke tempat tinggalnya. Program vaksinasi lansia dengan kunjungan langsung ke rumah perlu ditingkatkan agar vaksin dapat menjangkau sasarannya,” kata Soegianto Ali dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya. Selain vaksinasi, hal penting yang perlu disadari banyak pihak adalah fenomena dimensia alzheimer di kalangan lansia. “Dimensia alzheimer pada lansia tidak hanya merupakan isu kesehatan, tetapi juga social dan ekonomi,” demikian dinyatakan oleh Yuda Turana dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya. “Bayangkan seorang lansia 70 tahun penderita dimensia hidup bersama dengan anaknya yang berusia antara 30-40 tahun, serta cucunya yang mungkin berusia 5-10 tahun. Anak yang masih berusia produktif terbeban untuk merawat anaknya yang berusia sekolah, belum mandiri, tetapi juga harus mengurus lansia dengan demensia alzheimer dalam kurun waktu sekitar tahun,” lanjutnya. Sementara itu, “obat yang efektif belum juga ditemukan,” kata Yuda Turana. Outlook ini menunjukkan estimasi kasus demensia di Indonesia beberapa tahun lalu sekitar 1,2 juta pasien dan diperkirakan akan melonjak menjadi lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2050. Meskipun data nasional belum ada, data penelitian di Jogjakarta menunjukkan sekitar 20 persen lansia yang disurvei mengalami gangguan kognitif yang sudah mengganggu aktivitas hariannya. Selain itu, tercatat juga bahwa lebih dari 30 persen kasus demensia alzheimer disebabkan oleh faktor risiko gaya hidup, padahal gaya hidup ini dapat dimodifikasi. Riset Kesehatan Dasar terakhir yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 justru menunjukkan peningkatan berbagai faktor risiko demensia, seperti hipertensi, diabetes melitus, obesitas, merokok, dan kondisi inaktivitas. Dalam hal teknologi bagi lansia, Outlook ini membawa kabar baik. Selain teknologi di bidang kesehatan terus membaik dalam hal deteksi dan pelaporan hasil, teknologi pemantau aktivitas lansia terus mengalami perbaikan. Saat ini telah berkembang teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR). “Dengan sensor LiDAR ini aktivitas lansia dapat dipantau tanpa menampilkan 100 persen citra tubuhnya,” kata Nova Eka Budiyanta, dosen Fakultas Teknik Unika Atma Jaya. “Jadi, privasi lansia akan tetap terjaga,” demikian Nova. Sensor LiDAR bekerja dengan memproduksi titik-titik koordinat pada ruang dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D). Dengan begitu penampakan yang dihasilkan oleh sensor LiDAR hanya berupa gabungan titik-titik yang menggambarkan keberadaan dan gerakan lansia di dalam ruangan, bukan citra utuh selaiknya kamera CCTV. Outlook ini menggambarkan LiDAR amat mungin dikombinasikan dengan Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Thing (IoT), sehingga di masa depan seorang lansia dapat terpantau aktivitasnya secara realtime dan respons yang diberikannya pun juga jauh lebih cepat. Outlook juga membahas dimensi psikososial lansia. Dipaparkan dalam Outlook bahwa hingga saat ini lansia masih mendapat stigma negatif. Menjadi tua sering dikonotasikan sebagai lemah, sakit, dan mendekati liang kubur. Kata ‘jompo’ kerap digunakan oleh masyarakat untuk menegaskan konotasi negatif itu. Bahkan, ‘panti jompo’ juga dipandang sebagai `tempat pembuangan’. Padahal, ‘panti jompo’ sendiri amat potensial berperan sebagai tempat interaksi dan komunikasi di antara warga lansia yang sebaya. Selain itu, tempat dan fasilitas publik saat ini juga belum ramah lansia. Pada saat yang sama, ageism tak jarang disematkan pada lansia. Ageism adalah diskriminasi negatif pada warga lansia. “Ageism sering ditemui di dunia kerja. Hanya karena seseorang berumur di atas 60 tahun, misalnya, ia tidak lagi diperbolehkan untuk bekerja. Padahal, yang diperlukan adalah apakah lansia mampu mengerjakan pekerjaan itu secara aman dan tanpa paksaan,” demikian dinyatakan oleh Eunike Sri Tyas Suci dari Fakultas Psikologi. “Untuk menghindari diskriminasi pada lansia ini,” lanjutnya, “sudah saatnya pertimbangan kompetensi dan kualifikasi (merit system), bukan usia, dikedepankan.” Outlook ini juga secara khusus menggagas tawaran ‘pengampuan parsial’ dari dimensi hukum. Berbeda dengan pengampuan maksimal yang membatasi gerak-gerak lansia–bahkan mencabut hak lansia–sebagai subyek hukum, Outlook ini menawarkan model pengaturan yang tetap menghargai lansia sebagai subyek hukum. “Pengampuan parsial,” menurut Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dari Fakultas Hukum, “adalah suatu model perlindungan hukum bagi warga lansia yang terukur.” “Warga lansia sebagai penerima pengampuan diberi
Malam Penganugerahan Frans Seda Award 2021

Unika Atma Jaya, Yayasan Atma Jaya, dan Frans Seda Foundation bekerja sama untuk membangun tradisi menganugerahkan Frans Seda Award (FSA) kepada pelaku perubahan masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya hendak mengenang, tetapi juga membagi dan menyebarluaskan pandangan hidup Frans Seda yang bernilai bagi bangsa. Award yang tahun ini telah memasuki tahun kelima diberikan kepada mereka yang telah bekerja nyata serta memberi dampak positif dan siginifikan pada masyarakat. Tahun 2021 ini FSA menetapkan tema “Sinergitas Pendidikan dan Kesehatan Saat dan PascaPandemi: Pendidikan dan Kesehatan bagi Semua”. Tema ini tidak saja sejalan dengan prinsip RPJMN 2020-2024, RKP 2021 dan 2022, tetapi juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ketiga (kesehatan) dan keempat (Pendidikan) yang telah diimplementasikan pula oleh pemerintah dan pelaku-pelaku pembangunan non-pemerintah di pusat dan di daerah. Penganugerahan ini adalah bagian dari upaya anak bangsa untuk memberi sumbangan nyata pembangunan yang terus berjalan. Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, sekaligus fondasi yang lebih dalam tentang dunia pendidikan dan kesehatan Indonesia saat ini dan masa depan bagi pemenang Award, termasuk juga bagi seluruh undangan acara penganugerahan ini, pandangan dari otoritas pendidikan dan kesehatan menempati kedudukan yang penting. Pandangan ini juga mempertemukan relasi antara dinamika di tingkat makro nasional dan global dengan tindakan-tindakan di tingkat mikro dan lokal. Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan adalah otoritas yang amat tepat untuk ditempatkan dalam kedudukan ini. Dalam hubungan ini, Unika Atma Jaya, Yayasan Atma Jaya, dan Frans Seda Foundation mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, BA, MA, serta Bapak Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, untuk memberikan Short Ministerial Talks dalam acara penganugerahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021. Publikasi
Peluncuran Buku Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis. Webinar: Arah Pengaturan Fintech di Indonesia

Pakar cyber law Unika Atma Jaya, Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. telah menulis dan menerbitkan buku yang berjudul Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis (Penerbit Atma Jaya). Buku ini merupakan kontribusi nyata dalam mengawal pesatnya pertumbuhan dan kompleksitas pengaturan industri teknologi finansial (fintech). Sebagai sektor yang terus bertumbuh dan bersinggungan dengan banyak aspek lain seperti perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen, acara peluncuran buku ini akan membahas “Arah Pengaturan Fintech di Indonesia”. Pendaftar akan memperoleh E-Book Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis secara GRATIS. Penanggap: Moderator: Penyelenggara Publikasi:
Alat Ukur Saintifik: Solusi Penyelesaian Masalah HAM di Industri Kelapa Sawit

Pendahuluan Status Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia tidak serta merta sejajar dengan pemenuhan hak dan keadilan terhadap para pekerjanya. Pekerja di perkebunan kelapa sawit sangat rentan terhadap ketidakadilan, mulai dari persoalan rendahnya upah dan hak ekonomi lainnya, tidak terpenuhinya hak sosial-budaya seperti kondisi kesehatan yang memprihatinkan, hingga kerusakan lingkungan sekitar perkebunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Fakultas Hukum (FH) Unika Atma Jaya dan Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) — bekerja sama dengan ICCO Cooperation — meluncurkan alat ukur yang dapat mengukur pemenuhan hak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Harapannya, alat ukur ini dapat digunakan untuk mengkaji pemenuhan ketiga hak tersebut oleh perusahaan kelapa sawit — dan sektor perkebunan lainnya secara umum. Ketidakadilan yang Tidak Kunjung Selesai Pekerja perkebunan kelapa sawit seringkali digambarkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak dari mereka yang tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terhadap eksploitasi, ruang kerja yang tidak ramah perempuan, perampasan tanah yang kerap kali terjadi, hingga kerusakan lingkungan yang tidak lagi terelakkan. Terlebih lagi, lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan peraturan khusus pekerja perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus memperkuat status quo yang diskriminatif dan tidak adil ini. Persoalan ini tentu tidak sehat bagi para pekerja, dan semakin ironis ketika Indonesia sebagai anggota dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Kovenan Hak Sipil dan Politik terlihat tidak serius dalam menyelesaikan masalah ini. Berbagai fakta yang menunjukkan bahwa terjadi praktik pekerja paksa di industri perkebunan kelapa sawit, di mana status mereka yang tidak jelas membuat upah yang diterima terlampau sedikit, kapasitas pekerjaan yang berlebihan, dan keselamatan kerja mereka yang minim — atau bahkan tidak dijamin sama sekali. Tidak hanya pekerja, masyarakat sekitar perkebunan juga terkena dampak dari operasi industri yang tidak ramah lingkungan, hingga sewenang-wenang merampas tanah milik masyarakat sekitar. Maka dari itu, rasanya mutlak untuk terus mencari keadilan, dan alat ukur ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan yang konkrit. Harapan di Tengah-tengah Ketidakadilan Alat ukur ini disusun agar dapat digunakan oleh masyarakat umum hingga lembaga sosial yang bergerak di bidang HAM untuk dapat mengevaluasi secara empiris dunia usaha dan peraturan negara. Penyelesaian pelanggaran HAM dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dapat segera diintervensi oleh alat ukur ini. Tidak hanya alat ukur, tim peneliti juga meluncurkan modul yang berisi langkah-langkah dan kondisi yang harus dipenuhi dalam menggunakan alat ukur tersebut dalam prakteknya. Pengumpulan data dan proses pengembangan alat ukur ini melibatkan pendapat para ahli hingga aktivis HAM melalui Focus Group Discussion (FGD) dan kajian literatur sebagai representasi atas metode kuantitatif dan kualitatif. Tim peneliti juga tidak luput melakukan validasi data dengan cara menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada berbagai aktor yang mengikuti tes, dengan tujuan mendapatkan masukan atau pendapat berdasarkan keahlian dan pengalamannya. Langkah Selanjutnya untuk Masa Depan Program ini mendapatkan respon positif dari kelompok masyarakat — lokal maupun nasional — yang bergerak di bidang HAM karena sangat relevan dengan data dan analitik situasi HAM di Indonesia. Dengan kondisi sumber daya material yang tidak banyak dimiliki oleh masyarakat sipil, sulit bagi mereka untuk dapat mengakses data yang terbatas dan mahal, ataupun instrumen saintifik lainnya. Program ini tentu dijangka akan meruntuhkan “tembok pembatas” tersebut dan dapat dipergunakan segara agar masyarakat sipil setempat dapat menganalisis situasi mereka tentang hak asasi manusia atau ketidakadilan sosial. Setelah alat ukur tersebut selesai disusun, tim peneliti melakukan berbagai macam terobosan untuk memperkenalkan secara luas alat ukur ini melalui berbagai cara, meskipun terhambat dengan kondisi pandemi. Tim peneliti melakukan Sosialisasi Publik melalui Webinar yang bekerjasama dengan GeoLive dan wadah siniar sebagai media partner. Policy Brief juga dilakukan dalam rangka menyampaikan kebijakan yang lebih baik dalam menangani pelanggaran HAM di industri kelapa sawit. Pengembangan ini juga akan terus berjalan dengan dihadirkannya situs web dengan maksud membangun dashboard yang tidak hanya menjangkau khalayak ramai, tetapi juga menjadi alat pendukung bagi studi serupa di masa mendatang. Kami yakin bahwa alat ukur ini merupakan satu langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah HAM.