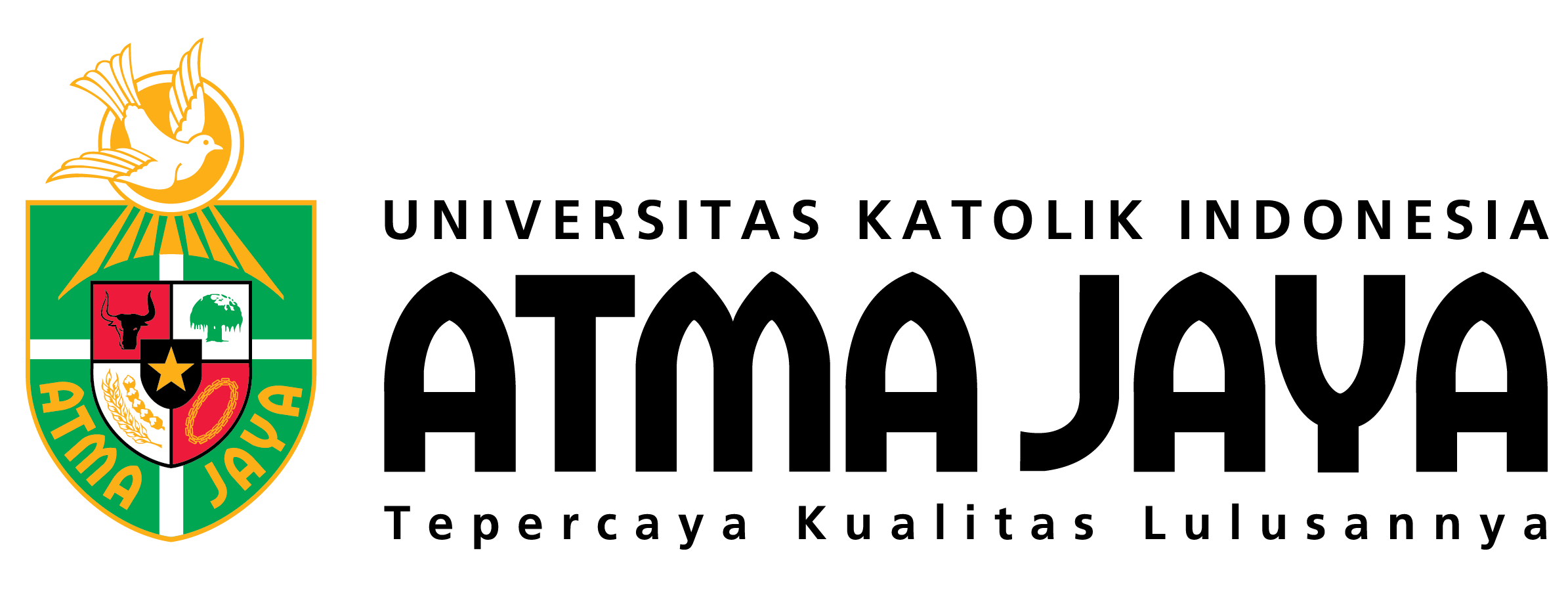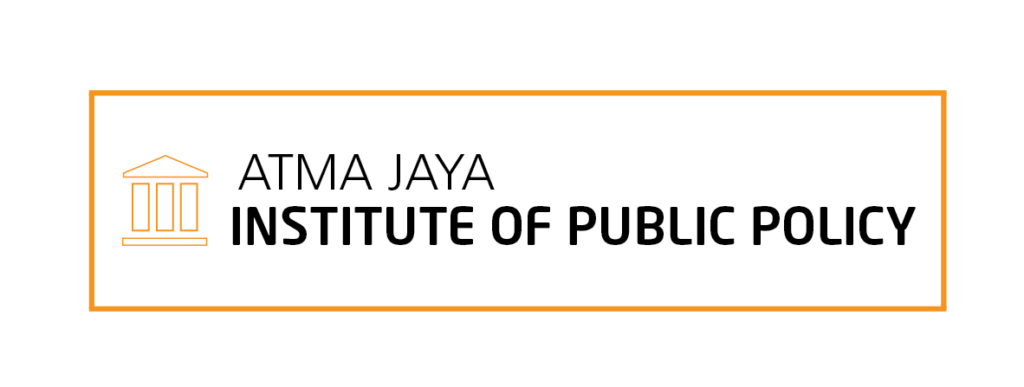Unearthing the Relationship Between Women Living in Mining Areas and Their Political Participation in Indonesia: The Dataset
This study examines the impact of mining industries on women’s political participation in Indonesia. Mining regions, often characterized by male-dominated labor structures and economic dependency on extractive industries, create socio-political barriers that limit women’s engagement in formal politics and decision-making processes. This research investigates how the presence of mining activities influences women’s political agency, leadership opportunities, and representation in local governance. Using a mixed-methods approach, the study analyzes national-level electoral data to compare women’s political participation in mining and non-mining districts. Additionally, qualitative case studies from selected mining regions explore the socio-economic and institutional constraints faced by women in pursuing political roles. Key factors examined include patriarchal norms, economic reliance on extractive industries, environmental activism, and policy frameworks that either enable or restrict women’s political involvement. The results indicate that while mining regions present significant structural barriers to women’s political participation, they also serve as spaces for emerging grassroots mobilization, particularly in environmental advocacy and community governance. This research contributes to the broader discourse on gender and resource politics by providing policy recommendations to enhance women’s representation in extractive economies.
Alat Ukur Saintifik: Solusi Penyelesaian Masalah HAM di Industri Kelapa Sawit

Pendahuluan Status Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia tidak serta merta sejajar dengan pemenuhan hak dan keadilan terhadap para pekerjanya. Pekerja di perkebunan kelapa sawit sangat rentan terhadap ketidakadilan, mulai dari persoalan rendahnya upah dan hak ekonomi lainnya, tidak terpenuhinya hak sosial-budaya seperti kondisi kesehatan yang memprihatinkan, hingga kerusakan lingkungan sekitar perkebunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Fakultas Hukum (FH) Unika Atma Jaya dan Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) — bekerja sama dengan ICCO Cooperation — meluncurkan alat ukur yang dapat mengukur pemenuhan hak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Harapannya, alat ukur ini dapat digunakan untuk mengkaji pemenuhan ketiga hak tersebut oleh perusahaan kelapa sawit — dan sektor perkebunan lainnya secara umum. Ketidakadilan yang Tidak Kunjung Selesai Pekerja perkebunan kelapa sawit seringkali digambarkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak dari mereka yang tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terhadap eksploitasi, ruang kerja yang tidak ramah perempuan, perampasan tanah yang kerap kali terjadi, hingga kerusakan lingkungan yang tidak lagi terelakkan. Terlebih lagi, lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan peraturan khusus pekerja perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus memperkuat status quo yang diskriminatif dan tidak adil ini. Persoalan ini tentu tidak sehat bagi para pekerja, dan semakin ironis ketika Indonesia sebagai anggota dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Kovenan Hak Sipil dan Politik terlihat tidak serius dalam menyelesaikan masalah ini. Berbagai fakta yang menunjukkan bahwa terjadi praktik pekerja paksa di industri perkebunan kelapa sawit, di mana status mereka yang tidak jelas membuat upah yang diterima terlampau sedikit, kapasitas pekerjaan yang berlebihan, dan keselamatan kerja mereka yang minim — atau bahkan tidak dijamin sama sekali. Tidak hanya pekerja, masyarakat sekitar perkebunan juga terkena dampak dari operasi industri yang tidak ramah lingkungan, hingga sewenang-wenang merampas tanah milik masyarakat sekitar. Maka dari itu, rasanya mutlak untuk terus mencari keadilan, dan alat ukur ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan yang konkrit. Harapan di Tengah-tengah Ketidakadilan Alat ukur ini disusun agar dapat digunakan oleh masyarakat umum hingga lembaga sosial yang bergerak di bidang HAM untuk dapat mengevaluasi secara empiris dunia usaha dan peraturan negara. Penyelesaian pelanggaran HAM dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dapat segera diintervensi oleh alat ukur ini. Tidak hanya alat ukur, tim peneliti juga meluncurkan modul yang berisi langkah-langkah dan kondisi yang harus dipenuhi dalam menggunakan alat ukur tersebut dalam prakteknya. Pengumpulan data dan proses pengembangan alat ukur ini melibatkan pendapat para ahli hingga aktivis HAM melalui Focus Group Discussion (FGD) dan kajian literatur sebagai representasi atas metode kuantitatif dan kualitatif. Tim peneliti juga tidak luput melakukan validasi data dengan cara menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada berbagai aktor yang mengikuti tes, dengan tujuan mendapatkan masukan atau pendapat berdasarkan keahlian dan pengalamannya. Langkah Selanjutnya untuk Masa Depan Program ini mendapatkan respon positif dari kelompok masyarakat — lokal maupun nasional — yang bergerak di bidang HAM karena sangat relevan dengan data dan analitik situasi HAM di Indonesia. Dengan kondisi sumber daya material yang tidak banyak dimiliki oleh masyarakat sipil, sulit bagi mereka untuk dapat mengakses data yang terbatas dan mahal, ataupun instrumen saintifik lainnya. Program ini tentu dijangka akan meruntuhkan “tembok pembatas” tersebut dan dapat dipergunakan segara agar masyarakat sipil setempat dapat menganalisis situasi mereka tentang hak asasi manusia atau ketidakadilan sosial. Setelah alat ukur tersebut selesai disusun, tim peneliti melakukan berbagai macam terobosan untuk memperkenalkan secara luas alat ukur ini melalui berbagai cara, meskipun terhambat dengan kondisi pandemi. Tim peneliti melakukan Sosialisasi Publik melalui Webinar yang bekerjasama dengan GeoLive dan wadah siniar sebagai media partner. Policy Brief juga dilakukan dalam rangka menyampaikan kebijakan yang lebih baik dalam menangani pelanggaran HAM di industri kelapa sawit. Pengembangan ini juga akan terus berjalan dengan dihadirkannya situs web dengan maksud membangun dashboard yang tidak hanya menjangkau khalayak ramai, tetapi juga menjadi alat pendukung bagi studi serupa di masa mendatang. Kami yakin bahwa alat ukur ini merupakan satu langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah HAM.
Pandangan Kaum Muda Perkotaan terhadap Demokrasi pada Tahun Politik 2019

Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) telah mengadakan sebuah survei dengan 1.388 responden anak muda dari Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Survei ini merupakan hasil kerja sama AJIPP dengan Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Atma Jaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi kaum milenial dan generasi Z terhadap demokrasi. Hasil survei ini menunjukkan bahwa 65% responden merasa mutu demokrasi di Indonesia termasuk buruk dan sangat buruk. Ketika ditanyakan lebih lanjut, 45% dari responden tersebut merasa penyebabnya adalah politisasi agama, sementara 22% menyalahkan hoax, 17% korupsi, dan 11% radikalisme. Keterangan selengkapnya bisa diunduh di pranala berikut: http://wwwprev.atmajaya.ac.id/filecontent/ipp-Rilisrisetpandangankaummillenialperkotaan.pdf