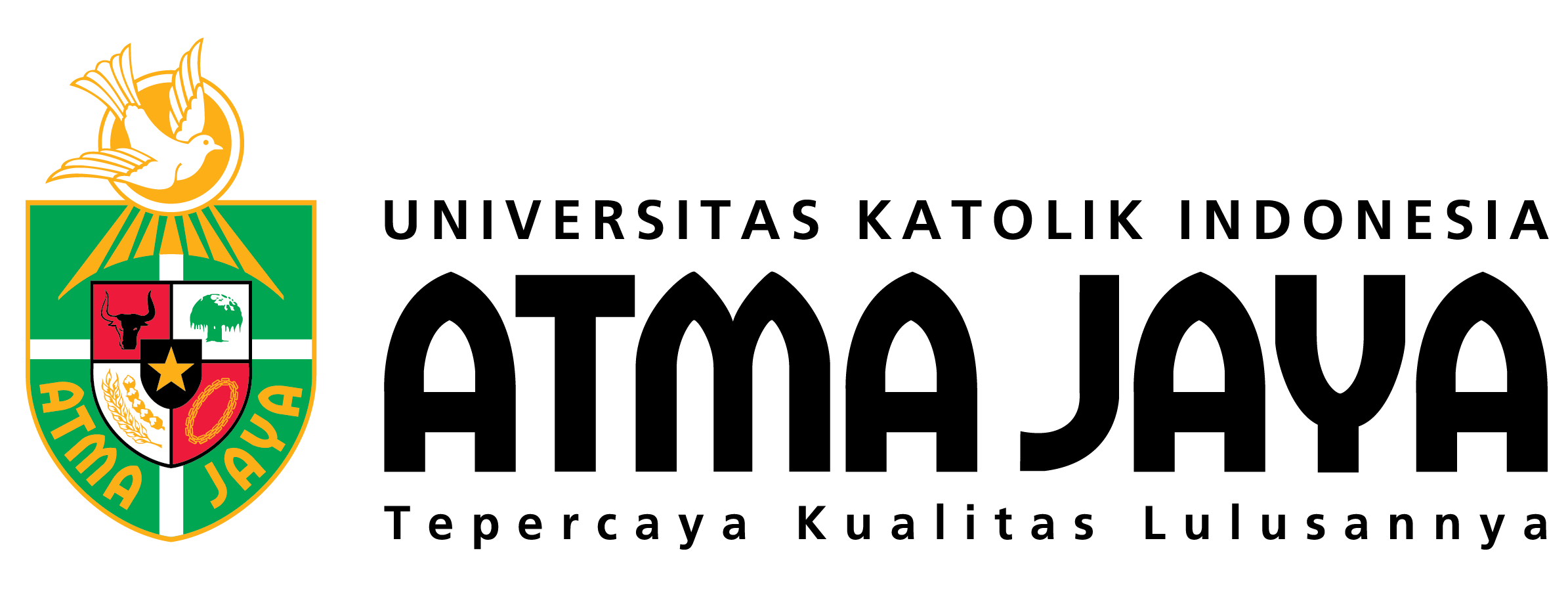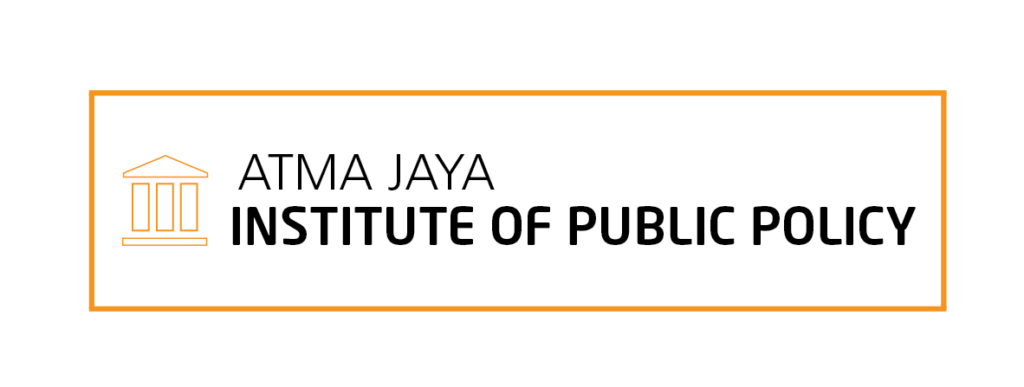Energi Alternatif Jangan Diabaikan
Penulis: Muhammad Nusyamsyi Editor: Fuji Pratiwi JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) prihatin terhadap kondisi udara ibu kota negara. Karena itu, APCNGI menyarankan agar penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan tidak diabaikan. Berdasarkan aplikasi air visual dengan air quality Index atau indeks kualitas udara, wilayah DKI Jakarta pada beberapa minggu terakhir berada di level rata-rata di atas 150 yang mana masuk dalam kategori tidak sehat, bahkan sempat menduduki peringkat nomor satu kota terpolusi dunia. Ketua umum APCNGI Robbi R Sukardi mengatakan, sudah hampir satu decade APCNGI mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya mengupayakan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan. BBG dinilai merupakan bahan bakar ramah lingkungan. “Namun, belakangan ini, BBG seakan mulai diabaikan.” ujar Robbi saat media briefing yang digelar APCNGI bersarna Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya saat menyoroti permasalahan polusi udara di DKI Jakarta di Unika Atma Jaya, Jakarta, Senin (5/8). Robbi mencontohkan, bus Transjakarta (TJ) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel solar yang diklaim telah memenuhi standar Euro4. Namun, kenyataannya TJ tidak menggunakan BBM diesel solar nonsnhsidi, seperti Pertamina Dex High Quality yang memiliki batas ambang sulfur di 50 ppm atau setara yang dapat memenuhi standar Euro-4 tersebut. “Salah satu penvumbang polusi udara terbesar adalah gas buang kendaraan bermesin diesel yang masih mengacu ke standar Euro-2 di Indonesia,” kata Robbi. Oleh karena itu, kata Robbi, BBG perlu tetap dijadikan salah satu langkah yang cepat dalam mengurangi polusi udara untuk saat ini. Hal ini sembari mempersiapkan energi alternatif rang lain, seperti kendaraan listrik, bahkan kendaraan berbahan bakar hidrogen yang masih membutuhkan waktu lagi. “BBG dan energi alternatif lainnya seharusnya berjalan beriringan,” ujar Robbi. Sekretaris Jenderal APCNGI Edhit A Hidayat mengatakan, saat ini di wilayah DKI Jakarta terdapat 23 lokasi pengisian BBG yang beroperasi, tujuh stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dalam perbaikan dan/atau belum dioperasikan, dan delapan SPBG yang masih dalam tahap perencanaan. “Meskipun jumlah infrastruktur pengisian BBG baik yang dibangun BUMN dan swasta telah tersedia, dari informasi yang APCNGI peroleh, utilisasi atau volume penjualan ke kendaraan berada di level rata-rata di bawah 30 persen secara keseluruhan,” ujar Edhit. Selain utilisasi yang masih rendah, kata Edhit, pemerintah pusat perlu segera menyelesaikan masalah ketetapan keekonomian dari usaha SPBG yang wajar. Hal itu guna mendorong lebih banyak peran swasta dalam menyedialcan infrastruktur SPBG. Kendaraan pengguna BBG yang merupakan salah satu solusi tersebut selayaknya dipertahankan dan dilaksanakan secara simultan. “Sambil juga pengembangan alternatif energi ramah lingkungan lainnya. bukan malah diabaikan. bahkan untuk dilupakan,” kata Edhit. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Java Irenius Dwinanto Bimo mengatakan, peran pemerintah tidak hanya sebatas keluarnya regulasi. Menurut Bimo, saat ini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah. tapi tidak efektif berjalan. AJIPP berpendapat, semua pengembangan kendaraan-kendaraan berbasis bahan bakar ramah lingkungan sangat baik bagi masyarakat. Karena itu, harus didukung segenap pelaku industri otomotif, masyarakat, dan pemerintah. “Tetap perlu pemikiran logis agar pencapaian tujuan supaya polusi udara dapat ditangani secara cepat, optimal, dan efektif.” kata Bimo. Artikel ini diterbitkan di koran Republika edisi Selasa, 6 Agustus 2019
Partisipasi Masyarakat Tinggi Mengawal Suara
3/6/2019 Jakarta, 29 Mei 2019 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan brownbag discussion membahas mengenai penerapan teknologi dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu. “Saat ini media banyak membahas mengenai dinamika politik pemilu, jarang yang membahas mengenai teknologi dalam pemilu. Padahal saat ini kita sedang mengalami revolusi industri 4.0, sehingga topik ini sangat penting untuk didiskusikan,” papar Edbert Gani Suryahudaya, direktur AJIPP. Diskusi tersebut mengundang Elina Ciptadi, salah satu co-founder dari kawalpemilu.org, dan Surya Tjandra, seorang dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dan juga politisi PSI. Kawalpemilu.org merupakan situs pengawasan penghitungan pemilu yang dikelola oleh masyarakat awam dan mengandalkan data berupa foto lembar C1 yang diambil oleh relawan. “Yang unik dari Indonesia adalah proses hitung suara pemilu di awal. Ketika suara pemilu sedang dihitung di masing-masing TPS, disaksikan oleh masyarakat dan ditentukan sah atau tidak juga bersama-sama. Ini menarik, menjadikan penghitungan suara pemilu milik bersama,” papar Elina Ciptadi. “Saat ini kita menunggu sebulan untuk mengetahui hasil pemilu. Bayangkan jika proses penghitungan setelah TPS, pelaporan, tabulasi, dan rekapitulasi dilakukan secara otomatis dengan komputer. Berapa banyak sumber daya yang bisa kita hemat?” tantang Elina. Surya Tjandra kemudian memberikan suntikan diskusi menarik bahwa belum adanya dasar hukum yang kuat untuk penghitungan suara pemilu menggunakan teknologi. Adanya kawalpemilu menunjukkan bahwa masyarakat awam pun bisa mengawasi jalannya pemilu dengan memanfaatkan teknologi. Antusiasme masyarakat juga tinggi untuk ikut berpartisipasi. Dalam pemilu 2019, terdapat lebih dari 40.000 relawan, 750 moderator, dan 1,3 juta web visitor kawalpemilu. “Antusiasmenya tinggi, tapi tingkat literasi data di Indonesia masih rendah. Dalam beberapa kasus, ada masyarakat yang masih menanyakan kesimpulan hasil pemilu, padahal semua data sudah dipublikasikan di situs KPU dan kawalpemilu.” Literasi data menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan tanggung jawab bersama. Surya kemudian menggarisbawahi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengawan pemilu, “Proses digitalisasi sangat baik. Ya artinya iya, tidak ya tidak. Tidak ada daerah abu-abu. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu, ada pengaruh sentimen dalam pemilu yang tidak bisa ditangkap oleh teknologi. Sejak 2014, politik identitas lahir di Indonesia dan sangat mempengaruhi proses pemilu kita. Bagaimana cara mengawasi dan mengantisipasinya?” Untuk pemilu berikutnya, Elina menyatakan tidak ada rencana untuk memformalisasi kawalpemilu. “Personil kami memiliki pekerjaan lain selain dari kawalpemilu. Akan menjadi sulit pengelolaannya jika kawalpemilu dijadikan organisasi resmi. Selain itu, karena personil kami sukarela, semua kegiatan dilakukan dengan hati senang,” papar Elina. Untuk pemilu selanjutnya, Surya juga menyarankan diadakannya pengawasan proses pemilu lain selain penghitungan. Pengawasan pemilu memang belum sempurna. Terlepas dari berbagai perhatian tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kawalpemilu merupakan angin segar dalam pemanfaatan teknologi dalam pemilu Indonesia. Situs ini juga membuktikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses demokrasi di Indonesia. Diskusi ini dapat diakses via: https://www.youtube.com/watch?v=Am4pd3tl-cs
Ringkasan Eksekutif Kajian Kesiapan Kaum Muda dan Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi

Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) telah mengadakan survei mengenai pandangan kaum muda khususnya milenial perkotaan mengenai bonus demografi. Menindaklanjuti survei tersebut, AJIPP menyelenggarakan brownbag discussion dengan mengundang empat politisi milenial dengan tema “Politisi Milenial Menjawab Tantangan Bonus Demografi”. Hasil kajian mengenai kesiapan kaum muda dan pemerintah menghadapi bonus demografi terangkum dalam sebuah ringkasan eksekutif yang dapat diunduh di sini: http://wwwprev.atmajaya.ac.id/filecontent/ipp-executivesummary.pdf
Director of AJIPP Talked about What to Expect After Election

What to expect after the election Edbert Gani Suryahudaya Jakarta Looking at the quick and real counts that are still progressing, the composition of legislative seats for the next five years is becoming clear. There will be no new party working in Senayan. The Hanura Party is the only party within the government coalition that is unlikely to get any seats. The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) will keep its power as the biggest party, while NasDem will enjoy a significant increase of votes. However, the political dynamics in the legislature will be much different compared to 2014. When elected in 2014, President Joko “Jokowi” Widodo did not have a majority in the House of Representatives. It took him over a year to reconfigure the balance of power among political parties and gather support to confidently start making policy decisions. Jokowi will most likely have a stronger grip on the House from the very start of his second term, thanks to his success in moving certain pivotal points among political actors beforehand. His coalition is likely to exceed 50 percent of the vote in the legislative election. The Legislative Institutions Law (MD3 Law) combined with the soon to be announced election result will provide his group large control over the seats of legislative speakers. With such strong support in the House, Jokowi has all the power he needs to further a progressive policy agenda. In consolidating his power, Golkar’s political maneuvers over the past three years have been particularly significant to Jokowi’s strategy. After having won the second largest share of votes in the 2014 election (14.75 percent) for the then-Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ticket, Golkar transitioned into becoming a pivotal player for Jokowi’s coalition. While giving Jokowi additional power in the Cabinet, Golkar was also valuable in driving support for Jokowi in the 2019 election by leveraging its vast political network and campaign machine. Following several corruption cases involving party leaders such as Setya Novanto and Idrus Marham, Golkar was surprisingly able to maintain its position as one of the top three parties. Although there may be several different explanations for that, being in the government coalition is likely to be one of the more dominant factors. Jokowi and Airlangga Hartarto, the new Golkar chairman and industry minister, were often seen making public appearances together. Their closeness can be seen to have benefited both sides. Generally speaking, political support for Prabowo in 2014 that came from Golkar’s base has shifted to Jokowi, thus helping Jokowi’s national campaign team to cater to that portion of the electorate. This shows us that partnering with a player such as Golkar has been instrumental to the success of the 2019 election – Jokowi was able to leverage that partnership to attain his second term. So what can we expect from the other parties if we expect neither Jokowi nor Prabowo to run in the next election? The PDI-P has shown us before that some success can be achieved by being part of the opposition for two straight terms. After having been in the opposition and achieving only the third largest share of votes in 2009, it followed up by winning the next two elections in a row. On the other hand, the Democratic Party, the biggest winner of the 2009 election and led by ex-president Susilo Bambang Yudhoyono, experienced a considerable fall in its share of votes in 2014. This is often thought to have been caused by the rampant corruption during the end of the Yudhoyono government. The Democrats eventually chose to abstain from Jokowi’s coalition in 2014, leading to an even smaller share of votes in the 2019 election. These two past examples should alert other parties to strategically choose their side, especially for those outside of Jokowi’s coalition. Whatever happens in the House, the demand of distribution of power in Jokowi’s next cabinet might become more contentious. Following the unexpectedly positive results from Golkar and NasDem, they would likely demand a larger allocation of strategic Cabinet positions. Additionally, the National Awakening Party (PKB) and United Development Party (PPP) are likely to demand the same thing, claiming the credit for Muslim votes. aThus President Jokowi has two main options open. With a strong hold on the House, this is his chance to concentrate fully on the policy agendas with the help of a Cabinet full of technocratic ministers. On the other hand, he also has the opportunity to consolidate his power by currying favor with the different political parties vying for strategic positions in his Cabinet. Unlike his first term in 2014, Jokowi no longer needs to take the latter option. There is much progress to be done if he prioritizes his policy agenda. Indonesians have much to gain if he does not get lured into playing a Game of Thrones. The writer, a graduate of the London School of Economics and Political Science, is the director of the Atma Jaya Institute of Public Policy. The views expressed are his own. This article was published on The Jakarta Post Newspaper, 16th of May 2019. The online version can be accessed here: https://www.thejakartapost.com/academia/2019/05/16/what-to-expect-after-the-polls.html
AJIPP`s research fellow commented on the post election`s result announcement`s demonstration
24/5/2019 Protesters clash with police after Indonesian president’s reelection, leaving 6 dead JAKARTA, Indonesia — Six people were reported killed and hundreds injured Wednesday in violent protests over the reelection of President Joko Widodo, prompting authorities to restrict access to social media. Jakarta’s governor, Anies Baswedan, said he received information that six people died in the clashes, which were orchestrated by supporters of the losing candidate in April’s election, Prabowo Subianto, after the official results were announced. Indonesian police acknowledged fatalities and said they heard hospital reports of the six deaths, but they declined to confirm that number. Police said they were not responsible for the deaths. “There’s no way the state apparatus would kill the perpetrators,” said Indonesia’s security minister, Wiranto. Authorities said police were forbidden to use live ammunition against demonstrators. Police, however, used tear gas in central Jakarta amid scuffles between protesters and security forces. On Wednesday afternoon, Indonesia’s communication minister, Rudiantara, said access to social media would be restricted with immediate effect. The move made Indonesia the latest country to curb social media platforms after chaos and violence. “The limitations will be placed on the spreading of download and uploads photos and videos,” Rudiantara said. “Again, it’s temporary and in stages.” The restrictions appeared to apply primarily to the sharing of videos and photos over social media platforms such as Instagram and WhatsApp. Widodo, who was reelected president, said his country “will not tolerate anyone who interferes with our security and democratic processes.” The situation, he added, was under control. Thousands of protesters started had begun gathering in central Jakarta after an official vote count showed Widodo had won more than 55 percent of 154 million votes cast in the April election. This was his second win over Prabowo, a retired army lieutenant general who lost the presidential election to Widodo five years ago. With early results predicting a clear win for Widodo, his challenger alleged foul play in the voting despite a widespread consensus that the election had been largely well-run. On Tuesday, Prabowo continued to challenge the vote and vowed to take his case to the Constitutional Court. His supporters gathered Tuesday morning near the election supervisory agency in central Jakarta, where tensions have been running high since the election. Muslims are marking the holy month of Ramadan. After breaking their fast and attending evening prayers, more demonstrators appeared. Police said these protesters were violent, unlike earlier ones, and broke through security barriers protecting the election agency, throwing rocks and torching cars. Some threw molotov cocktails at a police dormitory, authorities said. Videos from Tuesday evening showed rioters throwing fireworks and pelting police with rocks. Police responded with tear gas and water cannons. “They were very brutal,” said Muhammad Iqbal, a spokesman for the Indonesian police. The protests were “by design,” he said, and “not spontaneous.” Local media reported hundreds of injuries and several fatalities, but Iqbal said police had yet to confirm a death toll. More than 40,000 police and army personnel were on duty to keep order in the city. Dedi Prasetyo, another spokesman for the national police, said more than 62 protesters were arrested. Among them were three people carrying guns on Tuesday who admitted they planned to use the firearms in demonstrations the next day, he said. Police also said rioters had smuggled rocks and fireworks into central Jakarta via ambulance overnight. Some demonstrators were caught with envelopes stuffed with cash, presumably to pay others to join them, police said. Authorities have characterized the demonstrations as orchestrated. The protests were organized by hard-line Islamic groups that have called for Prabowo’s supporters to come out in force to show their dissatisfaction with the results. The retired general had stoked nationalist and religious sentiment ahead of the vote, portraying himself as the only person capable of defending Islam in the majority-Muslim country. In recent days, police have arrested three pro-Prabowo activists on suspicions of treason, the Associated Press reported. Among them was a retired general and former commander of Indonesia’s special forces. Speaking Wednesday at a news conference — at the same time as the president — Prabowo seemed to imply that it was the police who had started the chaos. “We plead with the [state apparatus] not to hurt the people’s hearts, especially not to hit and shoot them,” he said. “If this happens again, we’re very worried that the tapestry of our nation will be broken and hard to fix.” Still, Widodo’s win and the smoothly run election mark the solidifying of democracy in Indonesia since the end of dictator Suharto’s rule in 1998. Indonesia and majority-Muslim Malaysia have both bucked regional trends, their democracies growing more resilient and entrenched as other countries in Southeast Asia slip further into authoritarian rule. “The reelection of Jokowi is worth applauding simply because it came via an electoral process untainted by executive interference,” said Lee Morgenbesser, an expert in Southeast Asian politics at Griffith University in Australia, using the president’s nickname. Morgenbesser, who studies elections under authoritarianism, noted that elections in countries including Cambodia and Thailand in recent years suffered from “severe problems of manipulation and misconduct.” “Given the long history of fraudulent elections in Southeast Asia, it is worth celebrating the rare moments when the will of the people is actually translated into a free and fair result,” he added. Widodo, a soft-spoken former furniture salesman, promised in a victory speech Tuesday to be a protector to all Indonesians. He swept the vote in areas with large religious minority populations, notably the island of Bali and the Christian-heavy region of Papua. In his campaign, he emphasized infrastructure development and anti-poverty projects. Widodo’s victory five years ago generated no mass protests in Jakarta.This week’s demonstrations reflect the increasing confidence of hard-line groups after a string of victories, said Yoes C. Kenawas, a research fellow at Atma Jaya University’s Institute of Public Policy. Those wins have included the removal of a popular Jakarta governor, Basuki Tjahaja Purnama, in 2017 over a religious misstep.
Kuliah Umum Jeffrey Winters: Kondisi Terkini Demokrasi Indonesia

Jakarta, 11 April 2019 – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mengadakan kuliah akademik umum bertema “An Update on Indonesian Democracy”, dengan mengundang Jeffrey Winters. Adapun moderator untuk sesi tersebut adalah Yoes C. Kenawas, visiting research fellow di AJIPP, yang sedang mengambil gelar Ph.D di Northwestern University. Sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Bangsa ini. Pemilihan umum kali ini adalah keempat kalinya Indonesia secara langsung memilih presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini merupakan loncatan besar dalam demokrasi Indonesia. Lima belas tahun berselang dari pemilu pertama, bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia? Dengan maksud menjawab pertanyaan tersebut, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyelenggarakan kuliah akademik umum dengan mengundang Jeffrey Winters sebagai narasumber. Jeffrey Winters adalah Chair of the Department of Political Science dari Northwestern University. Winters mendalami bidang oligarki, demokrasi, dan ketidaksetaraan. Beliau terutama tertarik dengan kondisi politik di Indonesia dan Amerika Serikat. Kuliah akademik umum tersebut diadakan secara terbuka, dua minggu menjelang pemilu 2019. Dalam kuliah tersebut Winters memaparkan pandangannya mengenai kondisi oligarki dan demokrasi di Indonesia.
Berebut Generasi Digital

Oleh : Edbert Gani Alumnus The London School of Economics and Political Science, Inggris Direktur Atma Jaya Institute of Public Policy Salah satu daya tarik utama Pemilihan Umum 2019 ada di sekitar 85 juta pemilih muda, atau kurang lebih 45 persen dari total pemilik hak suara. Kami yang berada dalam rentang usia 18-36 tahun sering disebut sebagai pemilih milenial. Tak pelak, kata “milenial” mengalami inflasi dalam diskusi politik hari-hari ini. Karakteristik yang sering disematkan kepada kelompok ini antara lain adaptif dengan teknologi, melek digital, menyukai budaya pop, individualistis, dan narsisistik. Sayangnya, ciri khas ini masih disikapi para aktor politik sebagai kemasan semata, bukan substansi untuk mengirimkan pesan-pesan melalui kampanye. Alih-alih mencoba meraup dukungan generasi ini, mereka justru antipati terhadap kelompok pemilih tersebut. Maka tak aneh jika selisih elektabilitas pasangan calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-Ma‘ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, justru stagnan tiga bulan menjelang hari pemilihan. Meskipun stagnasi terjadi di hampir semua kelompok usia, kelompok milenial terlihat makin apatis. Penyebabnya, antara lain, polarisasi politik yang kian tajam di antara kedua kubu dan kejenuhan atas perdebatan politik yang minim kualitas. Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan lebih dari 60 persen publik mengaku kurang tertarik atau tidak tertarik sama sekali pada masalah politik. Sebuah angka yang cukup mencengangkan apabila kita percaya bahwa media sosial sesungguhnya berpotensi menjadi sarana komunikasi politik yang efektif dan sebagian besar pemilih punya akun media sosial. Kedua poros politik saat ini perlu menyikapi secara serius persoalan tersebut apabila mereka tidak ingin angka pemilih yang tak memilih alias golput, terutama di kalangan muda, meningkat. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita evaluasi bersama untuk menggairahkan kembali politik pemilihan, yaitu dari segi perspektif yang digunakan dalam melihat kelompok milenial serta strategi kampanye digital. Sebagian besar pemilih milenial yang akan mencoblos pada 17 April 2019 telah mencicipi pemilihan sebelumnya, baik di level daerah maupun di tingkat nasional. Sebagian kecil kelompok ini adalah pemilih pemula, yakni hanya 5 juta atau 6 persen. Maka pemilih milenial, yang umumnya kelompok terdidik, sudah memiliki kapasitas untuk mengevaluasi setiap calon berdasarkan pengalaman. Tim kedua calon mesti memikirkan tema kampanye yang bisa menggaet mereka agar bersedia datang ke bilik suara. Fakta membuktikan, generasi milenial adalah aktor ekonomi di berbagai industri. Agaknya unsur ini masih diabaikan tim kedua kandidat karena tema-tema kampanye masih berputar di sekitar kemasan, bukan program. Mereka bahkan cenderung menganggap pemilih muda sebagi aktor politik yang tak tahu apa-apa. Ironisnya, politikus muda yang terjun ke dunia politik praktis malah terbawa arus politikus tua, yang sangat kurang menyajikan konten politik mencerdaskan. Tak ada, misalnya, kampanye substantif tentang kebutuhkan riil pemilih muda seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, ekosistem bisnis, dan ruang terbuka bagi akses wawasan serta kreativitas. Padahal tak sedikit pemilih milenial adalah keluarga muda yang membutuhkan kepastian masa depan yang ditentukan oleh keputusan politik. Mereka bukan lagi penonton, melainkan kelas ekonomi utama yang akan menopang bonus demografi. Optimisme ekonomi ke depan sangat penting bagi pemilih dari kelompok ini ketimbang klarifikasi berbagai sensasi politik. Selain itu, kita dan para kator politik tanpa sadar terlalu memaksakan karakteristik milenial kelas menengah perkotaan (urban middle-class millennials) sebagai cerminan pemilih muda secara keseluruhan. Lebih dari itu, perkotaan dalam paradigman mereka yang tecermin dalam diskusi publik mengacu pada satu-dua kota besar saja. Kebutuhan kelompok milenial perkotaan berbeda dengan di perdesaan. Bahkan, meskipun sama-sama tinggal di perkotaan dan memakai smartphone, kaum milenial Jakarta memiliki kebutuhan yang jauh berbeda dibanding mereka yang ada di kota-kota di Sumatera, Kalimantan, atau Papua. Karena itu, sensitivitas pada isu-isu daerah tetap perlu untuk meraih suara kalangan milenial secara nasional. Lebih dalam lagi, keyakinan tim calon presiden yang mengerahkan pendengung (buzzer) di media sosial untuk mempengaruhi preferensi penghuninya perlu dipertanyakan. Apakah generasi milenial yang memakai Twitter, misalnya, akan terpengaruh oleh keriuhan percakapan yang mendominasi trending topic? Pengamatan saya di platform ini justru menemukan ketidaksinambungan sebuah topik populer dengan pengetahuan publik akan isu tersebut di lapangan secara umum. Sebut saja pelaku Twitter “asyik sendiri”. Keasyikan sendiri itu menular ke pembahasan di televisi. Para aktof politik dan redaksi menganalisis percakapan Twitter tentang tim mana yang menguasi tanda pagar tertentu. Padahal, berkaca pada besaran penggunanya, Twitter adalah platform minoritas dari sekian banyak media sosial yang populer di Indonesia. Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 8 Januari 2019 menunjukkan hanya 2 persen dari populasi pengguna Internet yang setiap hari atau hampir setiap hari membuka Twitter. Bahkan 89 persen responden mengaku tidak pernah memakainya. Dari data di atas terlihat bahwa meletakkan Twitter sebagai representasi percakapan digital masyarakat kita menjadi tidak relevan. Ini belum memasukkan unsur pengurangan jumlah user yang merupakan bot atau akun palsu. Terlebih apabila kita masih bergantung pada alat atau mesin deteksi yang dibeli dari perusahaan-perusahaan penyedia analisis media sosial dari negara lain yang memiliki bias tinggi terhadap bahasa percakapan dan minim pemahaman konteks politik nasional. Kepala tim digital Donald Trump pada pemilihan umum Amerika Serikat 2016, Brad Parscale, dalam sebuah wawancara di televisi mengungkapkan bahwa strategi yang ia pakai untuk menggaet pemilih di Internet adalah berfokus pada kelompok silent majority. Kelompok ini adalah pemakai media sosial yang tidak suka berdebat tentang sebuah topik atau tidak aktif memberikan komentar, tapi mereka menyimak isu-isu politik secara saksama. Kubu Demokrat Amerka pada waktu itu terkecoh dengan terlalu asyik meladeni cuitan provokatif Donald Trump sehingga luput memantau kebutuhan swing voter yang berada di Favebook dengan lebih dari 200 juta pengguna aktif per bulan – satu tingkat lebih banyak dari pemakai Facebook Indonesia yang berjumlah 130 juta dengan 84 juta di antaranya berusia milenial. Di luar soal sisi negatif pemakaian Facebook yang efektif menyebarkan berita bohong oleh kubu Trump, taktik mereka mendekati “pemilih diam” ini layak diperhatikan. Di Indonesia, upaya membidik kelas menengah milenial melalui media sosial perlu diimbangi dengan distribusi konten yang mencerdaskan. Kemenangan Emmanuel Macron di Prancis, atau dukungan anak muda kepada Partai Buruh Inggris, adalah contoh positif yang bisa kita ambil. Di Indonesia, keunggulan Jokowi mendapat suara dari kelompok milenial sekitar 52 persen sejauh ini menunjukkan respons positif pemilih muda terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, tim kampanye inkumben seharusnya memastikan sosialisasi kebihakan dan capaian ekonomi pemerintah yang berpengaruh langsung pada kelas ekonomi
Brownbag Discussion IPP Unika Atma Jaya: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Adalah Fokus Bersama
Bonus demografi yang sekarang kita nikmati bisa menjadi keuntungan bagi ekonomi namun dapat pula menjadi beban ekonomi. Karena itu diperlukan program yang jelas untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia terutama generasi muda. Jakarta, 22 Maret 2019 — Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) baru-baru ini menyelenggarakan diskusi yang melibatkan empat caleg dari generasi milenial. Keempatnya berasal dari empat partai politik yang berbeda. Mereka diantaranya Faldo Maldini, politisi PAN, Dedek Prayudi, politisi PSI, Khobbab Heryawan, politisi PKS, dan Puteri Komarudin, politisi Golkar. Selain mereka, panel diskusi yang lain adalah Andina Dwifatma, Dosen Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya, dan Edbert Gani Suryahudaya, Direktur Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP). Adapun moderator diskusi ini ialah Indro Adinugroho, dosen Fakultas Psikologi, Unika Atma Jaya. “Bonus demografi sudah mulai dari 2015 di Indonesia (menurut BPS). Puncaknya ada di tahun 2035. Hal ini bisa menjadi window of demographic disaster (meroketnya angka kriminal), atau menjadi window of opportunity (ketika mau investasi yang banyak pada sumber daya manusia). Hasilnya tidak bisa langsung dirasakan. Yang behasil contohnya RRC dan Korea. Kuncinya adalah pemberdayaan perempuan, pemberdataan pemuda, dan penghapusan pekerja anak,” papar Dedek ‘Uki’ Prayudi, politisi PSI. Dari diskusi tersebut tersimpulkan bahwa fokus dalam menunjang kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi milenial maupun generasi Z yang akan menjadi subjek pembangunan di era bonus demografi adalah tanggungjawab seluruh pihak. Adapun dari survei AJIPP terhadap kaum muda perkotaan, sebesar 63% menjawab yakin dapat bersaing secara global. Keyakinan tersebut perlu disambut dengan program-program yang bisa menyasar langsung pada minat dan bakat dari kaum muda. “Jadi negara industri. Basis knowledge. Bikin wadah. Berikan insentif untuk perusahaan yang memakai sumber daya dari rumah siap kerja,” papar Faldo Maldini, politisi PAN. “Pemerintah, sistem, sekarang hanya untuk menghindari disaster,” papar Khobbab Heryawan, politisi PKS. Selain fokus pada generasi muda di perkotaan, diskusi ini juga turut menyuarakan kepentingan membangun sumber daya manusia di daerah pedesaan. “Industri, yang daritadi kita bicarakan sudah masuk di RPJMN. Daritadi fokus kita ke kota, bagaimana dengan yang rural? Seperti misalnya dana desa, ini sudah bagus sekali. Selain itu tidak perlu juga saya rasa yang muda punya gagasan baru. Sekarang kebijakan yang bagusjuga sudah ada, kalo dilanjutin bisa maksimum. Yang penting kolaborasi muda dan tua.” Papar Puteri Komarudin, politisi Golkar. Selain itu, berkaitan dengan bonus demografi, berbagai program yang sedan atau akan dilaksanakan pemerintah perlu memperhatikan beberapa soal fundamental ekonomi. “Banyak tantangan yang perlu dihadapi agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana cara menarik sektor informal jadi formal? Hubungannya agar jaminan sosial bisa lebih mengakomodir tenaga kerja. Lalu keperluan riset dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, apa insentif yang akan diberikan ke perusahaan yang melakukan itu? Hal-hal ini yang perlu kita minta programnya ke partai politik dan calon penguasa,” papar Edbert Gani Suryahudaya, Direktur AJIPP. “Kalo mau merangkul milenial, kasih dong regulasi yang mendukung milenial,” ujar Andina Dwifatma, Dosen Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya. Acara dapat diakses di: https://www.youtube.com/watch?v=plgXX938wE4
In defence of Indonesias dull presidential debates
Indonesian democracy throws up many contrasts. The public have repeatedly shown that they have little faith in the key pillars of democracy, such as political parties and the House of Representatives. Yet public trust in democracy itself remains high, and turnout in elections remains strong. How do we explain this puzzle? Scholars suggest several factors are essential to the survival and deepening of democracy, for example, the presence of formal democratic institutions, accountability and transparency in democratic processes, and a consensus among elites to respect elections and democratic process as the only legitimate channels for changing leaders. In countries like Indonesia, where liberal democratic values have been eroding significantly over recent years, the repetitive performance of democratic “rituals” is crucial.The regular displays of these rituals help to shape the identity of Indonesian citizens — who are mostly sidelined during non-election periods — as members of a democratic society. This constructed identity, in turn, provides legitimacy to Indonesia’s electoral democracy. One of the most important rituals – beyond the elections themselves – is the regular presidential debates. But before we examine the debates in greater detail, it is important to take a closer look at the health of Indonesian democracy. Paradoxes in Indonesian democracy On the one hand, the public has a low level of trust toward pillars of Indonesia’s democracy. According to a survey by Charta Politika in 2018 in eight major cities in Indonesia, only 32.8 per cent of respondents said they trusted political parties, compared to 45.8 per cent who did not trust them. Further, in another survey by Charta Politika in 2019, only 0.6 per cent of respondents said that political parties had demonstrated good performance, and only 3.8 per cent said that the House of Representatives (DPR) was performing well. Other key pillars of democracy, such as the Supreme Court and the Regional Representatives Council (DPD), also ranked lowly. Only the office of president received a relatively high appreciation rate. The lack of connection between voters and parties is also concerning – only 19.5 per cent of respondents said they identified with a political party. Corruption by legislative and party members(link is external) is one cause of the low public trust toward political parties and the DPR. Indonesia’s electoral process is also flawed. Money politics and distribution of patronage(link is external) are common in both national and subnational elections. Meanwhile, the KPU is struggling with hoaxes and fake news(link is external) and constant bickering with the Elections Monitoring Body (Bawaslu)(link is external). These problems could cause public trust to further deteriorate. On the other hand, despite the low level of public trust of democratic institutions, the Indonesian electorate is highly supportive of democracy. A recent survey by the Indonesian Institute of Sciences (LIPI)(link is external) showed 73 per cent of respondents thought that democracy was the best system for the country, while 82 per cent said they believed Indonesia could be considered democratic. Turnout in national and regional elections is also comparatively high. In 2014, turnout in legislative and presidential elections was 75.1 per cent and 69.6 per cent, respectively. Likewise, in the 2018 simultaneous regional elections, average voter turnout was 73.24 per cent. Although turnout has been declining, it is still higher than many other democracies, including advanced ones like the United States. Presidential debates The presidential debates play an important role in maintaining these positive results. The KPU scheduled five televised presidential debates in this election season. They cover the most pressing issues in Indonesia, from the economy, to human rights, education, health, and terrorism. In each debate, candidates present their ideas on at least four general topics. For example, in the third debate on 17 March, the vice presidential candidates, Ma’ruf Amin and Sandiaga Uno, discussed their programs on education, health, human resources, and socio-cultural issues. Each debate lasts for about two hours, including breaks between sessions. Typically, each candidate has four minutes to present an opening statement on a particular topic. This is followed by an approximately eight-minute long session, during which each candidate must answer a question from a panel of experts, as well as comment on the opponent’s answer. When the time is up, the debate moves on to the next topic. In the third session, candidates are allowed to question their opponent about policies or plans to tackle certain issues. Finally, each candidate delivers a closing statement. Each debate presents a series of rituals, including singing the national anthem, reminders about the rules for the candidates and their supporters, a speech from the head of the KPU, and the repeated display of sealed envelopes containing the questions set by a panel of experts, to reinforce the transparency, accountability, and neutrality of the KPU. In the first two debates, the candidates selected the number of the envelope containing questions they would then answer, much like a beauty pageant. Given the limited time available for the discussion of complex issues, an apparent unwillingness to engage in fierce criticism, and the “unnecessary” rituals and debate policies set by the KPU, the first three debates disappointed many pundits and activists. Observers argue that the debates have lacked substance – the candidates did not exchange arguments but merely restated “old and recycled” policy rhetoric. As scholar Budi Irawanto said, the debates were “uninteresting, stiff, and scripted”. Public screenings Despite these disappointments, the debates remain necessary for the maintenance of Indonesia’s electoral democracy. The unnecessary rituals, the rather naïve rhetoric by the KPU chairman, the question and answer and debate sessions, and the public discussions after each debate all help to shape the identity of Indonesian people as members of a democratic society, however illusory that democratic identity may be. They create a sense of excitement and belonging in the electorate. Voters, however, are not passive recipients of these performative acts. The debates are important because for a brief moment during the long election season, voters feel that they are engaged in democracy. Many voters anticipate each debate, what the candidates will say, how
Transformasi Organisasi pada Era Milenial
Refleksi Karya “Transformasi Organisasi pada Era Milenial” diselenggarakan di Auditorium Gedung Yustinus lantai 15, Kampus 1 Semanggi Unika Atma Jaya. Kegiatan yang bertepatan dengan Dies Natalis Unika Atma Jaya ke-58 ini menghadirkan Ignasius Jonan (Menteri ESDM dan Dewan Penyantun Atma Jaya) sebagai keynote speaker, Mgr. Ignatius Suharyo (Uskup Agung Jakarta), dan Dr. Agustinus Prasetyantoko (Rektor Unika Atma Jaya) selaku moderator. Peserta dari acara ini adalah civitas academica Unika Atma Jaya mulai dari dosen, karyawan, beberapa perwakilan organisasi mahasiswa, dan tamu undangan guru dari beberapa sekolah-sekolah yang ada di sekitar Jakarta. Dalam kegiatan ini, para hadirin dapat belajar bagaimana struktur organisasi (termasuk di universitas) telah berubah pada zaman milenial ini, dan bagaimana mahasiswa dan tenaga pengajar dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan mempelajari bagaimana mengubah gagasan-gagasan menjadi tindakan-tindakan nyata di dalam kerangka organisasi untuk memajukan diri mereka sendiri dan juga apa yang mereka ingin perjuangkan. “Yang paling penting dalam keorganisasian adalah apa yang kita dapat, kita miliki, kita pelajari, dan itu bisa diubah menjadi aksi yang jelas.” – Ignasius Jonan, Menteri ESDM Indonesia